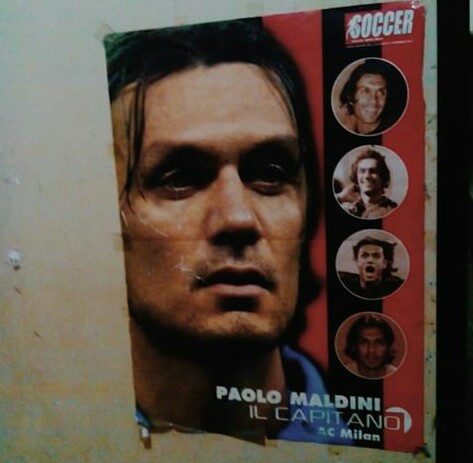Jika dalam sandiwaranya yang berjudul As You Like It Shakespeare menulis bahwa seluruh dunia adalah panggung, maka Steven Gerrard adalah lakon yang dapat membikin penontonnya tertawa.
Gelak tawa para penyaksi tak berhenti sampai hampir pada tahun ketujuh belas, walau tak tahu pasti sejak kapan tawa itu dimulai. Gerrard ada di atas panggung komedi. Komedi yang farce – yang seronok, yang membuat penontonnya terpingkal-pingkal.
Komedi farce yang pada era 1960-an pernah disepadankan oleh mendiang Motinggo Busye sebagai banyolan dapat diartikan sebagai lelucon atau jenis drama lucu yang dibedakan dari komedi biasanya karena cenderung lebih memperhatikan plot dibandingkan perwatakan. Jika melihat dari sejarahnya, farce, seperti halnya drama di awal tarikh Masehi sering dijadikan sebagai selingan pada saat menyampaikan pesan-pesan serius mengenai keselamatan dalam liturgi gereja. Fungsinya ini memang sesuai dengan asal katanya ‘farcire’, yang bermakna memasukkan hal-hal yang cenderung memberi rasa senang.
Bagi seorang dramawan ataupun pelakon komedi farce, kemampuan untuk meramu situasi yang sangat lucu adalah segalanya. Berbeda dengan drama yang lain, farce tidak pernah berusaha untuk menciptakan tokoh atau karakter tertentu – ia berusaha untuk menciptakan situasi. Situasi yang didramakanlah yang harus memancing gelak tawa para penonton. Secara kasat mata, tertawa memang aktivitas yang mudah untuk dilakukan. Ia tak serumit belajar atau sekhusyuk merenung – tapi coba ingat-ingat lagi, ada berapa banyak situasi yang begitu melekat pada ingatan karena menimbulkan tawa.
Lahir di Inggris – negara yang juga menjadi tanah air dramawan legendaris William Shakespeare – Steven Gerrard memang menjadi pelaku farce ulung. Laiknya seorang jenius farce, Steven Gerrard sadar bahwa tertawa yang laras dalam koridor komedi adalah tertawa yang dapat menelanjangi kebodohan, kesalahan dan kelemahan yang ada dalam setiap orang lewat situasi yang ia ciptakan di atas panggungnya – dan jika berbicara soal Gerrard, maka Liverpool adalah panggung.
Membicarakan komedi apalagi jika sadar bahwa kita masih hidup di negeri ini mau tak mau akan membawa kita kepada fenomena sajian komedi yang hanya menertawakan orang lain. Komedi yang hidup bahkan menjamur di sini adalah komedi yang cenderung menjadikan “cacatnya” orang lain sebagai hiburan – biasanya model yang diangkat sebagai tertawan adalah lakon-lakon pria yang kewanita-wanitaan – sehingga seolah-olah yang menertawakan adalah orang-orang yang bebas dari “cacat”, bebas dari kekurangan.
Sandiwara berjudul The Comedy of Errors milik Shakespeare adalah contoh farce yang perlu diingat. Alurnya biasa saja, bercerita tentang dua pasang orang berwajah sama dan bernama mirip yang memiliki seorang pelayan dan berada di satu kota sama. Mereka berdua masing-masing memiliki saudara kembar. Kembar identik yang juga memiliki pelayan yang mirip dengan pelayan dua pasang orang pertama. Pada intinya drama ini menceritakan tingkat kesalahan dan kebodohan manusia yang nyata dalam kehidupan. Sehingga dengan menonton dan menertawakan adegan-adegan dalam drama ini, penonton pun sebenarnya sedang menertawakan setiap kesalahan dan kebodohan yang ada pada mereka.
Di atas panggung Liverpool, ada banyak situasi yang diciptakan Gerrard lewat lakonnya. Lakonnya sebagai legenda hidup, lakonnya sebagai pesepak bola yang telah enam kali meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Premier League, lakonnya sebagai pesepak bola yang mencetak seratus delapan puluh gol bagi Liverpool namun belum pernah sekalipun mengangkat trofi Premier League.
Sekali lagi, farce tak bertujuan untuk menertawakan tokoh – ia bertujuan untuk menertawakan situasi. Lantas, sebagai pelakon farce panggung Liverpool, apa yang harusnya ditertawakan, apa yang harus ditelanjangi lewat tawa atas situasi yang diciptakan oleh Gerrard?
Gerrard sebagai aktor dari komedi farce yang dimainkannya memang kerap mengundang gelak tawa. Ia bukan pesepak bola sembarangan. Ia tak hanya menjadi bintang Liverpool – ia adalah pesepak bola yang memimpin Liverpool, terlebih lagi, ia adalah pesepak bola yang besar di Liverpool. Prestasinya juga tak sembarangan. Pesepak bola yang menyumbang sebelas trofi bagi klubnya tentulah bukan pesepak bola asal jadi dan asal tampan. Namun, atas satu hal yang sampai hari ini belum bisa diraihnya – ia menjadi tertawaan banyak penikmat sepak bola. Selebrasi mencium kameranya tentulah menjadi objek lelucon yang menyenangkan. Foto aksi mengangkat trofi Premier League dari pesepak bola yang menjadi rival klubnya yang dibubuhi tulisan seolah-olah sang rival sedang memaksa Gerrard untuk melihat baik-baik apa yang sedang diangkatnya tentulah menjadi banyolan segar yang entah berapa kali muncul di dunia maya.
Gerrard adalah ironi. Di satu sisi begitu mendamba trofi Premier League, di satu sisi ia sendiri pula yang membikin usaha untuk mewujudkan ambisinya berantakan lewat insiden terpleset yang termahsyur itu. Insiden yang terlihat sepele namun selalu diandai-andaikan agar tak terjadi.
Dalam esainya yang berjudul “Lantas, Apa Salahnya Ketawa?” Remy Sylado menjelaskan bagaimana komedi yang sebenarnya. Menurutnya, apa yang harus dimiliki oleh aktor dan aktris komedi – bukan pelawak – adalah kemampuan untuk menafsir naskah dengan menggunakan tubuhnya untuk menjadikannya sebagai seni peran yang presentasional. Sebuah seni yang bekerja dengan memadukan kata-kata lucu dan gerak-gerik jenaka yang dapat menjungkirbalikkan sebuah doktrin yang terlanjur menancap dalam kepala setiap orang. Misalnya, sadar atau tidak sadar, kita kerap didoktrin tentang menakutkannya sebuah kesalahan. Kesalahan sedikit bisa meluluhlantakkan apa selama ini dibangun dengan susah payah. Namun dalam komedi, kesalahan adalah hal yang paling sering ditertawakan. Sehingga bolehlah disimpulkan bahwa komedi yang paling laras itu adalah komedi mempertontonkan sebuah pertunjukan di mana aktor dan aktris yang ditertawakan oleh para penontonnya karena apa yang dibuatnya di atas panggung harus menjadi gambaran dari semua orang yang menonton pertunjukan itu. Komedi yang seharusnya bukanlah komedi yang menyajikan hal-hal yang membuat penontonnya menertawakan aktor dan aktrisnya semata, tetapi menertawakan kesalahan, kebebalan ataupun kebodohannya sendiri – menertawakan apa yang sebenarnya ada dalam hidup si penonton.
Sosok Gerrard yang entah sejak kapan menjadi begitu karikatural dan cepat memprovokasi gelak tawa, secara teori seharusnya menjadi wajah dari sepak bola itu sendiri. Jika selebrasi mencium kameranya mengundang olok-olok dengan dalih bahwa yang bisa diciumnya hanyalah kamera bukan trofi Premier League – barangkali sebagai aktor farce, Gerrard ingin menunjukkan bahwa seperti itulah sepak bola. Terkadang tak semua gelar bisa direbut. Ada begitu banyak kompetisi, ada begitu banyak peluang, ada begitu banyak kesempatan – namun yang namanya peluang, tentulah tak semuanya bisa berhasil diraih. Insiden terpeleset atau jadwal panjang duduk di bangku cadangan yang kerap menjadi bahan humor itu seharusnya menjadi gambaran bahwa sehebat apapun seorang pesepak bola, akan tiba masanya saat ia tak lagi menjadi pesepak bola yang istimewa. Gerrard mempertontonkan sebuah adegan saat superioritas seorang pesepak bola harus takluk oleh insiden terpeleset di lapangan. Gerrard sedang membawa para penontonnya untuk menyaksikan sebuah plot yang di mulai dari saat ia yang begitu akrab dengan lapangan dan puja-puja para penggemar sampai saat bangku cadangan dan olok-olok yang menjadi karibnya. Para penonton tertawa, terbahak-bahak sampai sakit perut.
Menyimpulkan perkataan Remy Sylado, jika tawa yang disajikan Semar, Petruk, Gareng ataupun Bagong sedikit banyak membantu Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa – maka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David De Gea, Manuel Neuer, Andrea Pirlo pun berutang banyak atas setiap gelak tawa yang ditujukan buat Steven Gerrard, gelak tawa yang sedikit banyak mengingatkan kalau akan tiba masanya mereka tak lagi jadi pesepak bola istimewa.
Tulisan ini pernah tayang di portal yang sekarang sudah jadi mendiang, ditulis saat Gerrard memutuskan hengkang dari ranah sepak bola Inggris.